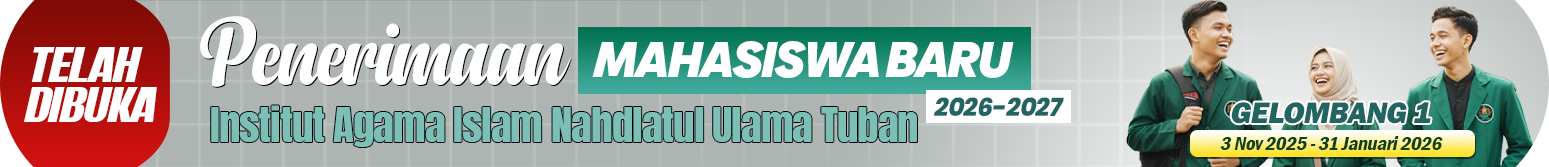Oleh : Aufi Imaduddin, S.H.I., M.H.
IAINUonline – Dua hari lalu, tepatnya Tanggal 3 Febuari 2026, Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., MS telah resmi pensiun dan berhenti dari jabatan hakim MK yang telah diembannya selama 13 Tahun.
Hal itu ditandai dengan ceremony Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi di Gedung MK pada 4 Februari 2026. Dengan begitu maka akan ada Pengganti Hakim MK yang baru untuk mengisi 1 kursi hakim yang kosong.
Setiap kali kursi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kosong, negara mendadak serius. Semua bicara konstitusi, etika, dan integritas. Kata-katanya tinggi, nadanya khidmat. Tapi seperti biasa, semakin sakral prosesnya, semakin minim ruang publik untuk ikut bertanya.
Apalagi soal pengisian hakim MK pengganti Arif Hidayat urusan penting yang terasa seperti rapat keluarga besar: banyak yang tahu, sedikit yang benar-benar dilibatkan.
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang seharusnya berdiri paling jauh dari kompromi kekuasaan. Tapi setiap kali kursi hakim MK kosong, satu pertanyaan selalu muncul dan jarang dijawab dengan jujur: apakah yang dicari benar-benar penjaga konstitusi, atau figur yang paling aman bagi penguasa?
Secara ideal, hakim MK itu penjaga konstitusi. Bukan penjaga perasaan, bukan penenang elite, dan jelas bukan penghalus kepentingan. Tapi dalam realitas politik kita, kriteria “penjaga konstitusi” sering diterjemahkan lebih sederhana: tidak ribet, tidak terlalu keras, dan tahu diri. Kalau bisa pintar, berpengalaman, dan… nyaman diajak kerja sama..
Lucunya, setiap calon yang muncul selalu punya CV sempurna. Semua ahli hukum, semua berintegritas, semua berkomitmen pada konstitusi. Seolah negeri ini hanya punya segelintir orang yang pantas, dan kebetulan mereka selalu berputar di lingkar yang sama. Publik pun hanya bisa mengangguk sambil bertanya pelan: ini seleksi terbuka atau arisan elite?
Yang bikin tambah pedas, prosesnya sering dibungkus dengan kalimat pamungkas: “sudah sesuai mekanisme.” Kalimat ini sakti. Bisa menghentikan diskusi, mematikan kritik, dan mengubah pertanyaan substansial jadi kesan “ribut tidak perlu”. Padahal, konstitusi tidak pernah meminta kita berhenti berpikir hanya karena prosedur sudah dijalankan.
Yang sering digaungkan justru kata-kata aman: pengalaman, rekam jejak, integritas. Semua calon pasti memilikinya setidaknya di atas kertas. Tapi publik jarang diajak menilai satu hal yang paling krusial: independensi nyata. Apakah calon hakim ini punya sejarah berjarak dengan kekuasaan? Atau justru terbiasa hidup nyaman di lingkarannya?
Mengisi hakim MK seharusnya jadi momen mencari orang yang berani bikin tidak nyaman. Tapi yang sering terjadi, justru dicari yang paling minim potensi konflik. MK idealnya tempat orang-orang yang berani berkata “ini inkonstitusional” meski semua tidak suka. Tapi bagaimana mungkin berharap keberanian, kalau sejak awal yang dicari adalah figur paling aman?
Pengganti Arif Hidayat seharusnya membawa energi baru bagi MK. Bukan sekadar melanjutkan kursi kosong, tapi menguatkan kepercayaan publik. Sayangnya, publik justru lebih sering disuguhi proses yang terasa tertutup, cepat, dan rapi, terlalu rapi untuk urusan sebesar menjaga konstitusi. Rapi seperti sudah tahu ujungnya ke mana.
Yang lebih ironis, kampus dan komunitas akademik sering dijadikan rujukan keilmuan, tapi jarang benar-benar diajak bicara saat keputusan dibuat. Padahal, mahasiswa tiap semester dicekoki teori checks and balances, independensi peradilan, dan judicial review. Di kelas, MK digambarkan agung. Di luar kelas, pengisiannya terasa… biasa saja.
Kalau hakim MK diisi dengan pendekatan “yang penting tidak bikin gaduh”, jangan heran kalau putusannya nanti dibaca dengan kacamata curiga. Wibawa lembaga tidak hanya dibangun dari palu sidang, tapi juga dari cara kursinya diisi. Konstitusi bukan benda mati yang cukup dijaga oleh orang pintar; ia butuh orang yang berani kehilangan kenyamanan.
Pada akhirnya, pertanyaan paling pedas bukan soal siapa yang terpilih, tapi untuk siapa ia akan berdiri ketika diuji. Untuk konstitusi, atau untuk stabilitas versi elite? Kalau sejak awal jawabannya sudah bisa ditebak, mungkin kita tidak sedang mencari hakim MK, kita hanya sedang mencari penyesuai konstitusi.
Dan di titik itu, konstitusi memang masih ada. Tapi penjaganya perlahan berubah fungsi: bukan lagi pelindung demokrasi, melainkan pengaman keadaan.
Tulisan kecil ini tidak sedang menolak siapa pun secara personal. Yang ditolak adalah cara berpikir bahwa konstitusi cukup dijaga oleh orang “yang tepat secara administratif”. Konstitusi butuh lebih dari itu. Ia butuh hakim yang siap tidak disukai, siap diserang, dan siap sendirian ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Sebagai akademisi kampus, kami percaya satu hal: hakim konstitusi tidak boleh dipilih dengan logika “yang penting aman”. Karena demokrasi tidak pernah aman. Ia selalu berisik, penuh konflik, dan menuntut keberanian.
Jika MK diisi oleh mereka yang lebih takut pada kegaduhan daripada pelanggaran konstitusi, maka masalahnya bukan lagi pada satu kursi kosong—melainkan pada arah demokrasi itu sendiri.