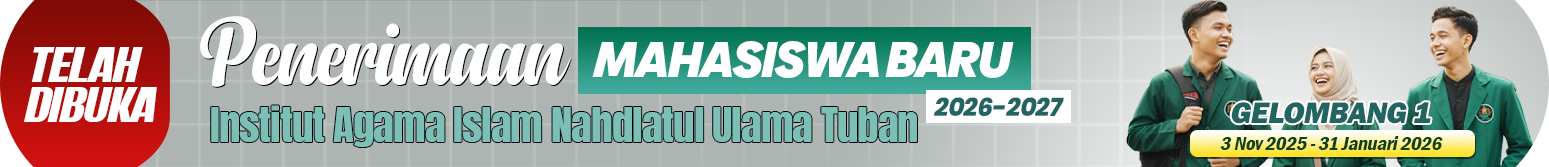Oleh: Muhammad Za’im Muhibbulloh
Strategi Damai dalam Perjanjian Hudaibiyah
Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk menunaikan umrah. Namun, kaum Quraisy menghalangi niat tersebut dan akhirnya disepakati Perjanjian Hudaibiyah, yang secara lahiriah tampak merugikan pihak Muslim.
Di antara isi perjanjian itu ;Umat Islam tidak diizinkan masuk Makkah saat itu, tetapi boleh kembali tahun depan. Sehingga kemudian ada gencatan senjata antara kedua pihak selama 10 tahun.
Siapa pun dari Quraisy yang melarikan diri ke Madinah harus dikembalikan, tapi sebaliknya tidak. Masing-masing pihak bebas menjalin persekutuan.
Namun, hal paling menyakitkan secara emosional adalah ketika Suhail bin Amr, wakil Quraisy, menolak redaksi pembuka surat perjanjian yang ditulis “Bismillahirrahmanirrahim“. Ia meminta diganti menjadi “Bismika Allahumma” sebagaimana tradisi Quraisy.
Lebih berat lagi, saat kalimat “Muhammad Rasulullah” ditolak. Suhail berkata, “Kalau kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, kami tidak akan memerangimu.” Akhirnya, atas arahan Rasulullah sendiri, kalimat itu diganti menjadi “Muhammad bin Abdullah”.
Para sahabat sangat kecewa. Umar bin Khattab bahkan sempat memprotes keputusan tersebut. Namun, Rasulullah SAW bersabda: “Aku adalah utusan Allah, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan aku.”
Terbukti, dua tahun kemudian Makkah ditaklukkan secara damai — kemenangan besar yang diawali dari keputusan strategis yang tampak seperti “mundur”.
Refleksi Perjanjian Hudaibiyah dalam Sejarah Indonesia
Semangat Perjanjian Hudaibiyah hidup kembali dalam sejarah Indonesia saat perumusan Piagam Jakarta pada tahun 1945. Naskah asli Piagam Jakarta mencantumkan kalimat:
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Namun, demi menjaga persatuan nasional yang terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa, tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada menerima penghapusan tujuh kata tersebut. Ini bukan keputusan mudah.
Sebelum menerima penghapusan tujuh kata tersebut, delegasi Islam — salah satunya KH. Wahid Hasyim — melakukan sowan kepada Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, untuk meminta pendapat dan restu.
Dalam hikmah dan kebesaran jiwa beliau sebagai ulama dan negarawan, KH. Hasyim Asy’ari merestui penghapusan kalimat tersebut dengan satu syarat penting:
“Asal Islam di Indonesia ini tetap bisa diamalkan dengan merdeka, tidak diganggu oleh pihak mana pun.”
Inilah bentuk ijtihad kebangsaan para ulama: “mundur” demi merajut persatuan dan keutuhan NKRI. Sebuah sikap visioner yang mewarisi semangat Hudaibiyah — bukan kalah, tapi menang dengan cara yang lebih damai dan mulia.
Pancasila dan Keutuhan Bangsa
Sikap bijak para pendiri bangsa dan ulama dalam menerima perubahan Piagam Jakarta menjadi wujud dari nilai-nilai Pancasila, khususnya: Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, diterima dalam bingkai kebhinekaan agama. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, ditegakkan di atas keberagaman. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai cita-cita bersama.
Penghapusan kalimat syariat bukan bentuk kekalahan Islam, tetapi strategi mulia untuk merajut kebersamaan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW di Hudaibiyah, para ulama dan tokoh bangsa telah “mundur selangkah” demi “maju sepuluh langkah” ke depan.
Sejarah telah mengajarkan bahwa kerelaan untuk mengalah demi kepentingan bersama adalah bentuk kemenangan yang sejati.
Dari Perjanjian Hudaibiyah hingga Piagam Jakarta, kita belajar bahwa kebesaran bukan semata pada siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling bijak menjaga masa depan umat dan bangsa.
Di tengah tantangan kehidupan berbangsa hari ini, semangat ini tetap relevan: Bersatu dalam perbedaan, maju bersama dalam kebinekaan.(*)