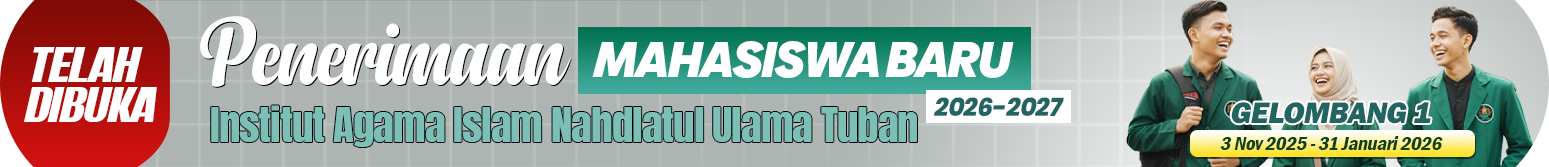Oleh : Fathul Amin
Di suatu sore yang teduh, dua orang duduk santai di pojok ruangan usai rapat yang cukup melelahkan. Segelas air mineral khas daerah Tuban hampir habis, dan meja masih penuh dengan berkas yang belum sempat dirapikan. Salah satu dari mereka, sambil meregangkan badan, berkata pelan, “Aku jadi ingat ucapan Sayyidina Ali: al-haqqu bilā nidhōmin qod yaglibuhu al-bāthilu bin nidhōm.”
Temannya menoleh, mengernyitkan dahi sejenak, lalu memberikan respon. “Kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir, ya? Pas sekali. Visi besar, niat baik, tapi masing-masing jalan sendiri.”
Ucapan itu menggantung di udara, lebih nyaring dari suara-suara diskusi tadi. Dari obrolan ringan itu, tersingkap realitas yang jauh lebih dalam: kebenaran bisa lumpuh, jika komunikasi dalam organisasi hanya jadi formalitas.
“Al-haqqu bilā nidhōmin qod yaglibuhu al-bāthilu bin nidhōm” — kebenaran tanpa sistem bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut menyentil realitas banyak organisasi saat ini, termasuk lembaga masyarakat, pendidikan dan sosial-keagamaan.
Dalam konteks organisasi modern, sistem yang dimaksud mencakup komunikasi yang terarah, struktur yang solid, serta koordinasi yang hidup. Ketika komunikasi melemah, masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya penyatuan gagasan, dan akhirnya gagal mencapai tujuan bersama dalam waktu yang direncanakan.
Sebesar dan sebaik apa pun visi organisasi, tanpa sistem komunikasi yang menyatukan langkah, organisasi itu akan rapuh. Banyak kegagalan tidak lahir dari kekurangan sumber daya atau ide, tapi dari kegagalan berkomunikasi. Di sinilah urgensi menjadikan komunikasi sebagai jantung organisasi, bukan sekadar pelengkap administratif.
Sejarah mencatat, salah satu contoh lemahnya komunikasi organisasi bisa kita lihat pada keruntuhan Daulah Abbasiyah di Baghdad pada abad ke-13. Saat pasukan Mongol menyerbu, pusat pemerintahan tidak mampu memberikan arahan yang jelas kepada wilayah-wilayah kekuasaan yang lebih kecil.
Masing-masing daerah bergerak sendiri, bahkan beberapa justru berkompromi dengan penjajah. Kelemahan ini bukan karena kurangnya kekuatan militer atau legitimasi kekuasaan, tetapi karena buruknya komunikasi dan koordinasi.
Contoh lain datang dari gerakan Pan-Islamisme di akhir abad ke-19. Meskipun memiliki semangat persatuan umat Islam melawan kolonialisme, gerakan ini tidak mampu menyatukan kekuatan karena miskinnya komunikasi antar pemimpin di berbagai negara.
Alih-alih bersatu, masing-masing tokoh membawa agendanya sendiri, dan tidak sedikit yang akhirnya terpecah karena kesalahpahaman. Semangat kebenaran dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dan komunikatif.
Di Nusantara, perjuangan melawan penjajah juga menyimpan kisah yang sama. Tanpa mengurangi rasa hormat dan memungkiri jasa perjuangan para pahlawan, beberapa perlawanan lokal yang heroik gagal mendapatkan dukungan luas karena tidak terhubung secara komunikasi.
Perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan tokoh-tokoh lainnya bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi. Kolonialisme membangun sistem informasi dan logistik yang kuat, sementara para pejuang berjalan dengan semangat tinggi tapi dengan jalur komunikasi yang sangat terbatas.
Pelajaran ini juga berlaku di era digital hari ini. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi tentang membangun pemahaman bersama. Ketika komponen organisasi tidak saling memahami tugas dan arah kebijakan, maka yang terjadi adalah kesibukan yang membingungkan. Masing-masing merasa sudah bekerja, tapi tidak ada hasil kolektif yang bisa dirasakan.
Dalam banyak lembaga, kerap terjadi tumpang tindih program, agenda yang saling bertabrakan, atau bahkan kebijakan yang berjalan di tempat. Penyebabnya bukan karena niat yang buruk, tapi karena saluran komunikasi tidak dibangun dengan baik. Koordinasi lintas unit tidak dibiasakan. Rapat sering menjadi formalitas, bukan ruang berbagi gagasan.
Jika komunikasi antarunit hanya berjalan satu arah, atau bahkan hanya seputar perintah teknis, maka tidak akan muncul inovasi. Organisasi tidak bertumbuh karena hanya menyampaikan, bukan mendengarkan. Di sinilah letak pentingnya komunikasi partisipatif, di mana semua lini merasa terlibat, terdengar, dan diberdayakan.
Kita perlu jujur mengakui bahwa sebagian program tidak berjalan bukan karena kurangnya SDM atau dana, tetapi karena miskomunikasi. Sebuah surat bisa sampai, tetapi maknanya tidak dipahami. Sebuah keputusan diumumkan, tapi tidak disosialisasikan. Akibatnya, ada jurang besar antara kebijakan dan pelaksanaan.
Sudah saatnya kita menata kembali sistem komunikasi organisasi, bukan untuk sekadar efisiensi, tetapi untuk menjaga semangat kolektif dalam bekerja. Kebenaran yang kita perjuangkan hari ini butuh sistem, butuh sinergi, dan yang terutama: butuh komunikasi yang sehat.
Mari kembali ke hikmah Sayyidina Ali. Organisasi kita harus menjadikan komunikasi sebagai sistem, bukan sekadar alat. Karena sekali lagi, kebenaran yang tidak terorganisir, akan selalu kalah oleh kebatilan yang disiplin dan rapi.(*)