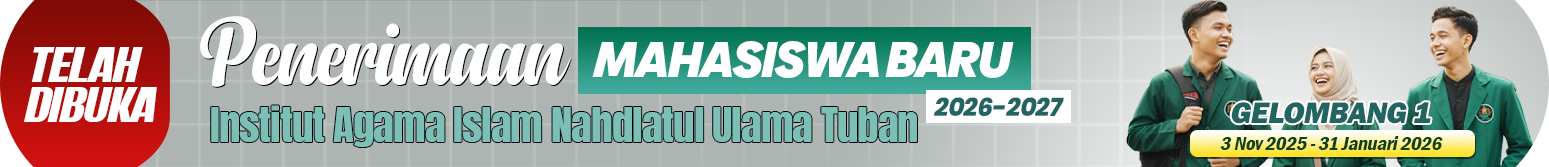Oleh : Fathul Amin
Di bulan Ramadan tahun ini masyarakat Indonesia sedang ramai membicarakan serial film asal Negeri Jiran yang berjudul Bidaah, serial ini disutradarai oleh Ellie Suriaty dan terdiri dari 15 episode dengan durasi sekitar 30 menit per episode. Bidaah tayang perdana pada 6 Maret 2025 di platform streaming Viu, dengan jadwal tayang setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Bidaah mengisahkan perjalanan Baiduri (diperankan oleh Riena Diana), seorang wanita muda yang hidup dalam keluarga yang sangat taat beragama. Suatu hari, ibunya, Kalsum (Fazlina Ahmad Daud), memaksanya untuk bergabung dengan sebuah kelompok keagamaan bernama Jihad Ummah, yang dipimpin oleh pria karismatik bernama Walid Muhammad (Faizal Hussein).
Awalnya, ajaran kelompok ini tampak religius dan meyakinkan. Namun, seiring waktu, Baiduri mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia menyaksikan praktik-praktik yang menyimpang, seperti pernikahan paksa, kewajiban patuh total kepada pemimpin, dan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Situasi semakin kompleks ketika Hambali (Fattah Amin), putra dari orang kepercayaan Walid, kembali dari Yaman dan mulai meragukan ajaran kelompok tersebut. Bersama Baiduri, mereka berusaha mengungkap kebenaran di balik Jihad Ummah dan melindungi keluarga mereka dari pengaruh sekte sesat tersebut.
Agama sejatinya hadir sebagai kompas moral, penerang jalan hidup, dan penguat jiwa manusia dalam menghadapi kerumitan dunia. Namun ironisnya, tidak jarang di tengah masyarakat, justru para tokoh agama — yang seharusnya menjadi penjaga kemurnian pesan ilahi — malah menjelma sebagai aktor utama dalam panggung kebohongan.
Dengan kecerdikan memainkan diksi-diksi dalil, dengan lihai menyusun narasi yang berbalut “ketakwaan,” tak sedikit tokoh agama yang secara halus maupun terang-terangan memanfaatkan kepercayaan umat demi menumpuk kepentingan pribadi: kekuasaan, kekayaan, popularitas, hingga kendali atas moral sosial.
Fenomena ini bukan sekadar penyimpangan individual, tapi penyakit sistemik dalam budaya beragama yang terlalu menggantungkan iman pada figur, bukan pada kebenaran itu sendiri. Di tangan tokoh-tokoh semacam ini, agama yang suci berubah menjadi instrumen manipulasi — mengunci akal sehat, memenjarakan kritik, dan melahirkan generasi yang takut bertanya karena telah diajari bahwa mempertanyakan “ustadz” sama dengan menggugat Tuhan.
Sama seperti Bidaah membuka mata penonton bahwa tidak semua yang berlabel agama adalah kebenaran, kritik ini mengajak kita semua untuk tidak silau pada simbol. Jubah, serban, panggilan “Kyai” atau “Ustadz” tidak selalu identik dengan keteladanan. Justru, sering kali di balik simbol itu tersembunyi ambisi, kepentingan, bahkan kejahatan yang rapi dikemas dalam ayat-ayat.
Sangat disayangkan kasus yang mirip dengan serial Bidaah ini terjadi di negeri yang kita kenal sebagai negara dengan jumlah warga muslimnya terbesar di dunia. Seperti yang diberitakan pada harian Tempo tanggal 2 Desember 2024 silam. Di sana ditulis Pimpinan sebuah Pondok Pesantren di Serang, Banten mencabuli santrinya hingga hamil.
Terungkap aksi pencabulan itu sudah terjadi sejak tahun 2021. Ia juga mengaborsi korban untuk menutupi perbuatan bejat tersebut. Hasil pemeriksaan Polisi yang memeriksa dari tiga santriwati yang diduga sebagai korban dari pimpinan sebuah pondok pesantren tersebut, terbukti pimpinan pondok pesantren itu melakukan tindak asusila terhadap ketiga santri tersebut.
Bahkan Kapolres Serang Ajun Komisaris Besar Condro Sasongko kala itu, pencabulan dilakukan terhadap 3 korban dalam rentang waktu yang berbeda. Salah satu korban mengaku empat kali dicabuli sejak 2021 hingga 2022. Sedangkan korban lainnya tiga kali dicabuli pada Juni 2023 di dalam Pondok Pesantren. Bahkan dia mengaku sempat hamil.
“Pelaku kemudian mengaborsi korban untuk menutupi perbuatannya,” ucap Condro seperti yang ditulis harian Tempo Senin, 2 Desember 2024.
Condro juga menjelaskan, tersangka mulanya menyuruh korban untuk membuatkan kopi, memijatnya, dan melakukan pengobatan. “Dirayu, diminta mijit, hingga dipaksa,” ujarnya.
Agama tidak pernah salah, tapi tafsir yang dimonopoli oleh kepentingan pribadi telah mencederai makna suci itu. Umat harus lebih kritis, bukan hanya taat. Menghormati bukan berarti membenarkan semua ucapan. Karena di zaman ini, yang suci bisa menjadi topeng, dan yang menegur dianggap sesat.
Sikap dan rerata masyarakat yang menghormati berlebihan, bahkan sampai mengkultuskan seorang tokoh agama, sering dimanfaatkan oleh tokoh agama yang tidak benar-benar menjalankan ajaran agamanya dengan baik.
Taklid atau ketawadhuan umat sering dimanfaatkan, dieksploitasi dan dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi yang tentu jauh dari ajaran agama yang dianutnya. Tak terhitung kasus-kasus penipuan dalam arti materi, pelecehan dan tindakan negatif lainnya, dari relasi guru-murid, kiai-santri, tokoh agama-umat, manjikan-karyawanza dan sebagainya.
Mari berani berpikir jernih, bahwa iman sejati tidak lahir dari pemujaan terhadap figur, tetapi dari pemahaman yang matang dan hati yang tulus mencari kebenaran. Jangan sampai agama yang seharusnya membebaskan, justru menjadi jerat baru di tangan mereka yang licik berselimut kesalehan.(*)