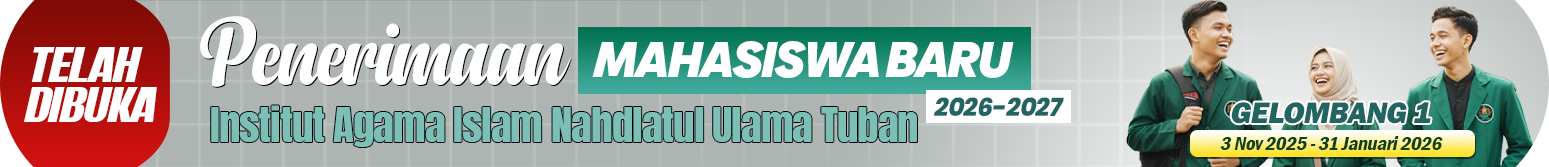Oleh : Auliya Urokhim M.A.
IAINUonline – Kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena, seharusnya tidak dibaca sebagai peristiwa tragis yang berdiri sendiri.
Di balik kisah memilukan itu, tersembunyi persoalan struktural yang lebih dalam yakni kegagalan negara memastikan pendidikan dasar benar-benar gratis, aman, dan bermartabat bagi seluruh anak Indonesia.
Kasus ini datang di tengah narasi resmi negara tentang pendidikan gratis, bantuan operasional sekolah, dan komitmen menghadirkan keadilan sosial. Namun fakta di lapangan berbicara lain. Ketika seorang anak kehilangan nyawa karena kebutuhan belajar paling elementer, klaim pendidikan dasar gratis patut dipertanyakan secara serius bukan sebagai slogan, melainkan sebagai realitas kebijakan.
Pensil, pena, dan buku bukan barang mewah. Barang tersebut adalah prasyarat paling dasar untuk bersekolah. Ketika kebutuhan sesederhana itu tak terjangkau, kita sedang berhadapan dengan kegagalan sistemik, bukan semata kesalahan keluarga atau individu.
Tragedi di Ngada menjadi cermin buram dari kebijakan pendidikan yang berhenti di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan.
Kemiskinan yang Tak Pernah Masuk Data
Kemiskinan tidak selalu tampil dalam angka statistik. Kefakiran itu kerap hadir dalam bentuk rasa malu, ketakutan, dan keterasingan. Banyak anak dari keluarga miskin menyimpan kecemasan setiap hari takut diminta membeli buku tambahan, khawatir diejek karena alat tulis seadanya, atau merasa tidak pantas berada di ruang kelas.
Tekanan psikologis semacam ini sering luput dari perhatian kebijakan pendidikan. Padahal, bagi anak-anak, rasa malu dan ketidakberdayaan bisa jauh lebih berat daripada beban akademik. Ketika tekanan itu menumpuk dan tak ada ruang aman untuk berbagi, tragedi menjadi mungkin.
Kasus di Ngada memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan, tetapi soal martabat. Negara boleh memiliki program bantuan pendidikan, tetapi jika mekanisme pendataan, distribusi, dan pengawasan lemah, bantuan itu tidak pernah benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Sekolah yang Belum Sepenuhnya Aman
Sekolah idealnya menjadi ruang aman dan setara bagi semua anak. Namun dalam praktiknya, sekolah sering kali mereproduksi ketimpangan. Berbagai kebutuhan tambahan seperti; buku pendamping, alat tulis, hingga akses digital kerap dibebankan kepada siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.
Ketika kebijakan pendidikan tidak sensitif terhadap kemiskinan, sekolah berubah dari ruang pembebasan menjadi ruang tekanan. Anak-anak miskin belajar lebih awal tentang rasa kalah, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kekurangan fasilitas.
Tragedi ini menegaskan bahwa akses pendidikan tidak cukup diukur dari angka partisipasi sekolah. Akses sejati berarti memastikan setiap anak dapat belajar tanpa rasa takut dan malu.
Pendidikan Gratis yang Teralienasi
Pemerintahan di era Prabowo Subianto menekankan pentingnya negara kuat, stabilitas nasional, dan efektivitas kebijakan. Namun tragedi di Ngada menunjukkan sisi lain dari wajah negara bahwa kebijakan yang teralienasi dari realitas paling dasar warga.
Alienasi kebijakan terjadi ketika keputusan publik dirumuskan jauh dari pengalaman hidup masyarakat rentan. Program berjalan, anggaran terserap, laporan disusun, tetapi luka sosial tetap menganga. Negara tampak hadir di pusat, tetapi absen di pinggiran.
Masalahnya bukan semata kekurangan anggaran, melainkan orientasi kebijakan. Ketika keberhasilan diukur melalui indikator makro dan simbol pembangunan besar, kebutuhan mikro seperti alat tulis anak sekolah terlewatkan.
Dalam logika semacam ini, anak-anak miskin menjadi korban dari pembangunan yang tidak memulai dari manusia.
Pesan Moral dari Sebuah Tragedi
Tragedi ini menyampaikan pesan moral yang sangat sederhana bahwa negara tidak boleh absen dari hal-hal kecil yang menentukan hidup warganya. Pensil dan buku adalah simbol dari kebutuhan dasar yang kerap diremehkan dalam perencanaan kebijakan. Ketika simbol ini gagal dipenuhi, jurang ketimpangan sedang menelan masa depan anak-anak.
Moralitas kebijakan tidak diukur dari seberapa lantang negara berbicara tentang kekuatan, melainkan dari seberapa sungguh-sungguh ia melindungi yang paling lemah. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang memastikan tidak ada anak merasa hidupnya tak layak dijalani hanya karena ia miskin.
Tanggung Jawab Kolektif yang Tak Bisa Dihindari
Mudah menyalahkan orang tua, sekolah, atau lingkungan. Namun tragedi ini adalah cermin kegagalan kolektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sipil berada dalam satu ekosistem yang saling terkait. Ketika satu bagian abai, dampaknya bisa fatal.
Pemerintah daerah perlu memastikan bantuan pendidikan benar-benar menjangkau keluarga miskin. Sekolah harus membangun mekanisme yang sensitif terhadap kondisi ekonomi siswa tanpa mempermalukan mereka. Negara, pada saat yang sama, harus berani mengevaluasi klaim pendidikan gratis secara jujur.
Seorang anak meninggal dunia karena tidak mampu membeli buku dan pena. Kalimat ini seharusnya cukup untuk membuat kita berhenti sejenak dan meninjau ulang makna pendidikan gratis yang selama ini dibanggakan. Tragedi di Ngada bukan sekadar berita duka, melainkan alarm keras tentang arah kebijakan pendidikan nasional.
Jika negara ingin menyebut pendidikan sebagai hak dasar, maka pemenuhannya tidak boleh berhenti pada spanduk dan jargon. Ia harus hadir nyata di tangan setiap anak bahkan yang paling miskin dan paling jauh dari pusat kekuasaan.
Sebab, kebijakan yang teralienasi dari kemanusiaan pada akhirnya akan selalu melahirkan luka. Dan luka yang dibiarkan, akan kembali mengetuk, dengan cara yang paling menyakitkan.