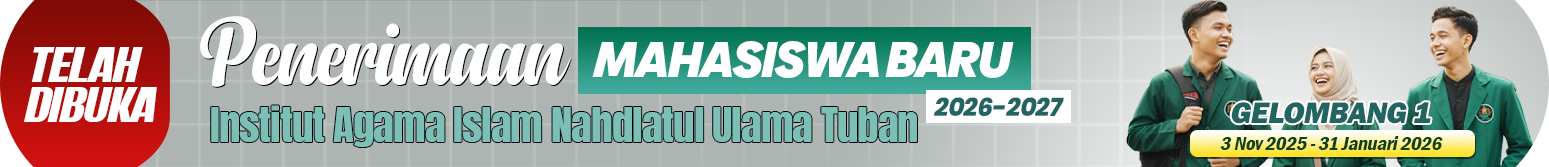Oleh : Diana Nur Indah Purnamasari, M.M
IAINUonline – “Tenang, masih ada waktu.”
Kalimat ini mungkin sering kita ucapkan, baik kepada mahasiswa maupun kepada diri kita sendiri.
Ada satu musim yang tidak tercantum dalam kalender akademik, tetapi selalu hadir setiap semester: Musim Deadline.
Tandanya mudah dikenali. Grup WhatsApp mendadak ramai apalagi disertai subjek “mohon segera” bermunculan. Kalender yang sebelumnya tampak longgar tiba tiba terasa sesak. Dan kita pun terdiam sejenak, “Oh iya ya, laporan itu…”
Menariknya, budaya deadline sering kita lekatkan pada mahasiswa. Kita menasehati mereka agar tidak menunda tugas, agar mencicil tugas yang kita berikan, agar disiplin waktu. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, bukankah kita juga kerap melakukan hal yang sama ?
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sebenarnya bisa diperbarui sejak awal semester baru disentuh ketika diminta dikumpulkan untuk divalidasi. Nilai yang bisa langsung diinput setelah ujian selesai justru rampung ketika sistem hampir ditutup. Proposal penelitian yang idenya sudah lama tersimpan, baru benar benar digarap saat pengumuman hibah hampir berakhir.
Mengapa kita begitu akrab dengan tenggat waktu?
Mungkin karena deadline bekerja seperti alarm darurat. Ia membangunkan fokus yang lama tertidur. Saat waktu terasa sempit, pikiran menjadi lebih tajam, kopi terasa lebih nikmat, dan pekerjaan seolah selesai lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ada sensasi dramatis ketika perasaan berhasil “menaklukkan” waktu.
Namun jika setiap pekerjaan selalu selesai di ujung batas, itu bukan lagi strategi produktif. Itu telah menjadi pola.
Sebagai pendidik, peran kita memang tidak tunggal. Kita mengajar, meneliti, mengabdi, membimbing, mengurus administrasi, menghadiri rapat, menyusun laporan, bahkan sering menjadi tempat curhat mahasiswa. Waktu terasa selalu kurang.
Akhirnya, kita cenderung memilih yang paling mendesak, bukan yang paling penting.
Di sinilah dampaknya mulai terasa bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada mahasiswa.
Beberapa waktu lalu, terdengar keluhan seorang mahasiswa. Nadanya bukan marah, lebih kepada lelah.
“Kenapa ya setiap ada informasi penting, selalu diberitahukan di hari H ? Kami jadi tidak punya waktu untuk bersiap.” Lalu ada yang menimpali kembali “Segala sesuatunya sudah disepakati tetapi kenapa malah berubah dalam sekejab”
Ini bukan tentang satu kali kejadian. Bukan pula soal informasi yang sifatnya mendadak karena keadaan darurat. Yang membuat mahasiswa itu kesal adalah pola yang berulang.
Bagi sebagian orang, mungkin ini terdengar sepele. Toh informasinya tetap sampai. Toh kegiatan tetap berjalan. Namun dari sudut pandang mahasiswa, hal itu membentuk satu pesan tersirat : ketidakteraturan adalah hal yang wajar.
Mahasiswa mungkin tidak melihat kita menyusun laporan hingga larut malam. Mereka tidak tahu tumpukan administrasi yang harus diselesaikan. Tetapi mereka merasakan ritme kerja kita.
Ketika perubahan jadwal disampaikan saat mepet, mereka yang sudah menyusun agenda, ada yang bekerja paruh waktu, mengikuti organisasi harus kembali menyesuaikan diri.
Kita berharap mahasiswa disiplin dan profesional, tetapi tanpa sadar kita sedang memodelkan kebiasaan yang berbeda.
Bekerja terlalu dekat dengan deadline juga mengorbankan ketenangan. Kita menjadi lebih mudah lelah, lebih cepat tertekan, dan kurang menikmati proses.
Lalu, apakah solusinya harus berubah drastis dan menjadi super disiplin dalam sekejap? Tidak juga.
Mungkin cukup dengan perubahan kecil namun konsisten.
Menjadikan deadline sebagai batas aman, bukan batas akhir. Jika laporan diminta tanggal 30, kita targetkan selesai tanggal 27. Tiga hari itu menjadi ruang bernapas. Jika ada revisi, kita punya waktu. Jika ada tugas mendadak, kita tidak panik.
Atau bisa mulai mengerjakan meski belum sempurna. Sering kali yang membuat kita menunda bukanlah malas, melainkan standar ideal yang terlalu tinggi. Kita menunggu waktu yang benar-benar senggang, namun sayangnya waktu itu jarang datang.
Refleksi tentang budaya deadline pada akhirnya bukan sekadar soal manajemen waktu. Ini soal kualitas profesionalisme dan budaya akademik yang kita bangun.
Kita mungkin tidak bisa menghapus deadline dari dunia akademik. Ia akan selalu ada. Namun kita bisa mengubah cara menyambutnya.
Bukan dengan kepanikan menjelang tenggat, tetapi dengan kesiapan yang lebih awal.
Bukan dengan perubahan jadwal mendadak, tetapi dengan perencanaan yang memberi kepastian. Siapa tahu, jika kita mulai berubah, musim deadline tidak lagi menjadi musim panik melainkan sekedar penanda bahwa satu fase kerja telah selesai dengan baik.