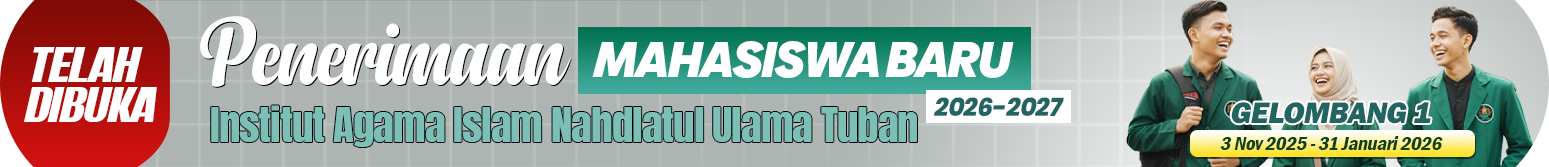Oleh : Drs. Fathul Amin, M.Pd.I.
IAINUonline – Suatu hari di dekat Masjid Nabawi, Umar bin Khattab duduk di bawah pohon kurma. Tiga pemuda datang tergesa. Dua di antaranya menggiring seorang pemuda lusuh.
“Tegakkan keadilan, wahai Amirul Mukminin! Qishashlah pembunuh ayah kami!”
Umar bangkit. “Benarkah engkau membunuh ayah mereka?”
Pemuda itu menunduk. “Benar.”
Ia bercerita singkat: unta miliknya merusak kebun seorang lelaki tua; lelaki itu menyembelih unta tersebut; amarah sesaat membuatnya mencabut pedang dan membunuhnya. Lelaki tua itu ternyata ayah dua pemuda yang kini menuntut qishash.
Umar menawarkan diyat dan meminta mereka memaafkan.
Kedua pemuda itu menolak. “Jiwa dibalas jiwa.”
Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata :”Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qishash atasku. Aku ridha dengan ketentuan Allah”, ujarnya dengan tegas.
“Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh tiga hari. Aku akan kembali untuk diqishash.”
“Mana bisa begitu?”, ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh.
“Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?”, tanya Umar.
“Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin”.
“Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggung jawaban kaumku bersamaku?”, pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar.
“Baik, aku akan memberimu waktu tiga hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu, agar kamu kembali untuk menepati janji.” kata Umar.
“Aku tidak memiliki seorang kerabatpun di sini. Hanya Allah, hanya Allah-lah penjaminku wahai orang-orang beriman”, kata dia.
Tetiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang :
“Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin.” Ternyata Salman al-Farisi yang berkata.
“Salman?” hardik Umar marah.”Kau belum mengenal pemuda ini, Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini”.
“Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, yaa, Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya”, jawab Salman tenang.
Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya.
Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah S.A.W. yang paling utama.
Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir, orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh.
Akhirnya tiba waktunya penqishashan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakkalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak, karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan.
Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali.
“Itu dia!” teriak Umar.
Dia datang menepati janjinya!.
Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar.
“Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin.” ujarnya dengan susah payah,
“Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu, Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa kutinggalkan lalu aku berlari dari sana.”
Demi Allah, ujar Umar menenanginya dan memberinya minum,
“Mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau bisa saja kabur dan menghilang?” tanya Umar.
“Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan Muslimin tak ada lagi orang yang menepati janji” jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum.
Mata Umar berkaca-kaca, sambil menahan haru, lalu ia bertanya:
“Lalu kau, Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?”
Kemudian Salman menjawab :
“Agar jangan sampai dikatakan, di kalangan Muslimin, tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya.”
Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar!
Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak.
“Saksikanlah wahai kaum Muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu.”
“Apa maksudnya ini?” Umar bertanya dengan tajam.
Kemudian dua pemuda menjawab :
“Agar jangan sampai dikatakan, di kalangan Muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya.”
Allahu Akbar! teriak hadirin.
Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang.
Kisah di masa Umar bin Khattab itu selalu terasa heroik. Seorang pemuda kembali untuk ditegakkan hukum atas dirinya. Salman al-Farisi berani menjadi penjamin. Dua anak yang kehilangan ayah memilih memaafkan. Amanah dijaga, janji ditepati, kepercayaan tidak dikhianati.
Namun ketika kisah itu selesai dibacakan, pertanyaannya tidak berhenti pada mereka. Ia berhenti pada saya.
Di perguruan tinggi, saya sering berdiri menyampaikan amanat. Saya berbicara tentang integritas, tentang komitmen akademik, tentang tanggung jawab moral.
Saya mengajak untuk menepati janji, disiplin waktu, menjaga etika ilmiah. Saya mendorong kolega untuk bekerja profesional, menjaga mutu, memperkuat institusi.
Tetapi jujur saja, tidak semua janji yang keluar dari lisan saya benar-benar saya tunaikan.
Ada rapat yang saya janjikan hadir tepat waktu, namun saya datang terlambat.
Ada program yang saya ucapkan akan saya kawal, namun saya biarkan tertunda.
Ada komitmen yang saya sampaikan dengan penuh keyakinan, tetapi pelaksanaannya melemah di tengah jalan.
Di sinilah kisah itu menampar pelan.
Pemuda itu kembali agar tidak hilang ksatria yang menepati janji.
Salman menjamin agar tidak hilang rasa saling percaya.
Dua pemuda memaafkan agar tidak hilang kasih sayang.
Lalu saya bertanya pada diri sendiri:
Jika saya terus mengucapkan amanat tanpa menunaikannya, apa yang akan hilang dari kampus ini?
Yang hilang bukan sekadar program.
Yang hilang adalah kepercayaan.
Perguruan tinggi dibangun bukan hanya oleh visi besar, tetapi oleh konsistensi kecil. Ia berdiri di atas budaya: budaya tepat waktu, budaya menepati komitmen, budaya menyelesaikan tugas sampai tuntas.
Ketika pimpinan atau dosen ringan berjanji namun berat melaksanakan, maka tanpa sadar ia sedang mengajarkan standar ganda kepada mahasiswanya.
Kita tidak mungkin menuntut mahasiswa disiplin jika kita sendiri longgar terhadap janji.
Kita tidak mungkin menanamkan integritas jika kita sendiri permisif terhadap kelalaian.
Kampus bukan hanya ruang transfer ilmu. Ia adalah ruang keteladanan. Saya mulai memahami bahwa amanat di perguruan tinggi bukan sekadar pidato pada momen formal. Amanat adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan.
Janji bukan sekadar retorika penggerak semangat, tetapi komitmen yang harus ditunaikan, meski lelah, meski sulit. Mungkin saya belum seteguh pemuda dalam kisah itu.
Mungkin saya belum seberani Salman. Namun setidaknya saya bisa mulai dari satu hal sederhana: mengurangi janji, memperbanyak realisasi. Karena perguruan tinggi tidak runtuh oleh kurangnya slogan, tetapi oleh rapuhnya integritas. Dan saya tidak ingin suatu hari orang berkata:
“Di kampus itu, amanat hanya tinggal kata-kata.”
Jika kisah itu mengajarkan bahwa janji bisa menyelamatkan kehormatan sebuah umat, maka di kampus hari ini, menepati janji bisa menyelamatkan martabat sebuah institusi.
Dan perubahan itu harus dimulai dari diri saya sendiri !!