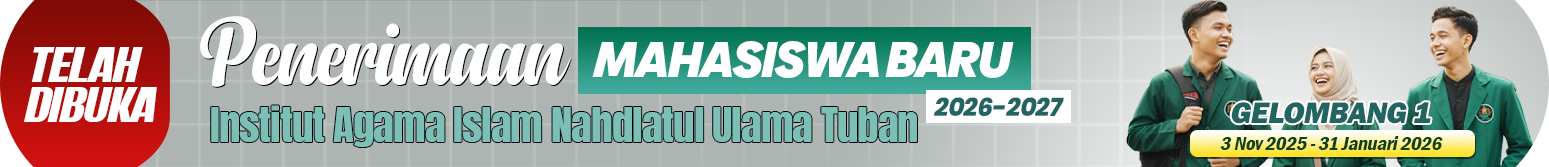Oleh : Moh. Arvani Zakky Al Kamil, M.Psi
IAINUonline – Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) kembali menempatkan relasi agama dan negara di pusat perhatian publik.
Di hadapan para kiai dan ulama serta jamaah mujahadah saat itu, Presiden tidak hanya menyampaikan laporan kinerja pemerintahan, tetapi juga membingkai kebijakan negara dalam bahasa moral dan religius.
Agama dihadirkan sebagai fondasi etis yang menopang agenda kesejahteraan nasional, mulai dari swasembada pangan hingga program bantuan sosial. Dalam konteks ini, pemuka agama tampil bukan sekadar sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai simbol legitimasi moral kekuasaan.
Relasi semacam ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia tidak pernah sepenuhnya sekuler, melainkan selalu berkelindan dengan nilai-nilai keagamaan. Politik membutuhkan bahasa etis agar diterima, dan agama menyediakan bahasa tersebut secara paling efektif.
Fenomena ini menjadi bentuk “kesucian politik”, yaitu kecenderungan negara meminjam simbol-simbol agama untuk membenarkan praktik kekuasaan, terutama di tengah krisis kemanusiaan (Andalas, 2008).
Dalam situasi ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakpastian global, negara tidak cukup berbicara dengan logika teknokratis semata. Ia memerlukan justifikasi moral agar kebijakan publik tampak sah dan bermakna. Di sinilah pemuka agama berperan sebagai mediator antara kekuasaan dan nurani publik. Namun, kesucian politik dapat berubah menjadi ilusi jika agama hanya menjadi alat legitimasi tanpa daya kritis.
Ketika agama berhenti bertanya dan hanya mengamini, maka politik kehilangan koreksi etis. Relasi yang tampak harmonis justru dapat menyembunyikan problem moral yang lebih dalam.
Dalam sejarah Indonesia, pemuka agama memiliki posisi strategis dalam membentuk orientasi politik masyarakat. Agama berfungsi sebagai sumber nilai yang memengaruhi perilaku politik individu dan kolektif (Sudrajat, 2002). Otoritas simbolik pemuka agama menjadikan mereka opinion leader yang mampu mengarahkan sikap publik terhadap negara.
Dalam masyarakat religius, suara kiai atau ulama seringkali lebih didengar dibandingkan pejabat formal. Hal ini membuat negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedekatan dengan tokoh-tokoh agama.
Kedekatan tersebut tidak selalu bermakna negatif, karena dapat memperkuat kohesi sosial dan stabilitas nasional. Namun, kedekatan yang terlalu rapat berisiko mengaburkan batas antara fungsi moral dan fungsi politis.
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola ketegangan tersebut. Islam kebangsaan yang dipraktikkan NU menempatkan negara sebagai instrumen, bukan tujuan akhir.
Negara dipahami sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat, sementara agama berfungsi sebagai penunjuk arah etis. Pendidikan Islam idealnya melahirkan kesadaran politik yang kritis, bukan loyalitas buta terhadap kekuasaan (Masamah, 2016).
Agama tidak boleh sekadar membentuk warga yang patuh, tetapi juga warga yang mampu berdialog dan mengoreksi. Dalam tradisi NU, pesantren dan jaringan kiai menjadi ruang pembentukan kesadaran tersebut. Mereka tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga nilai keadilan sosial dan tanggung jawab publik.
Politik kemanusiaan yang sering dikampanyekan negara umumnya tampil dalam bentuk kebijakan kesejahteraan. Program makan bergizi, bantuan sosial, swasembada pangan, dan perumahan rakyat menjadi indikator kepedulian negara terhadap rakyat.
Secara praktis, kebijakan ini memang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, politik kemanusiaan tidak hanya soal distribusi bantuan, melainkan juga soal pengakuan atas martabat dan hak-hak warga. Kemanusiaan tidak berhenti pada logika memberi, tetapi juga menuntut keadilan struktural.
Jika negara hanya berperan sebagai pemberi, sementara rakyat selalu ditempatkan sebagai penerima, relasi yang tercipta bersifat paternalistik. Dalam situasi ini, agama berisiko mengafirmasi ketimpangan dengan cara yang tidak disadari.
Bela agama tanpa membela manusia adalah kontradiksi etik. Inti ajaran agama bukan terletak pada simbol atau identitas, melainkan pada keberpihakan terhadap martabat manusia. Dalam konteks politik, hal ini berarti pemuka agama seharusnya berpihak pada korban ketidakadilan, bukan pada struktur kekuasaan.
Ketika agama lebih sibuk menjaga harmoni dengan negara dibandingkan membela kelompok rentan, maka agama kehilangan fungsi profetiknya (Haq, 2018). Fungsi profetik bukan sekadar menyeru kebaikan, tetapi juga berani menegur kekuasaan yang menyimpang. Agama yang diam terhadap ketidakadilan justru berkontribusi pada normalisasi penindasan.
Secara empiris, peran pemuka agama dalam kebijakan publik sangat menentukan. Pemahaman pemuka agama, baik pada aspek kognisi (pikiran), afeksi (perasaan), maupun konasi (kemauan/tindakan), memengaruhi sikap mereka terhadap regulasi negara (Elfiandri et al., 2015).
Kualitas sumber daya manusia pemuka agama turut menentukan bagaimana kebijakan diimplementasikan di tingkat akar rumput. Jika pemuka agama memiliki pemahaman kritis, kebijakan dapat dikoreksi secara konstruktif. Sebaliknya, jika pemuka agama bersikap pasif, kebijakan berjalan tanpa pengawasan etis.
Temuan ini menegaskan bahwa relasi agama dan negara bukan sekadar wacana normatif, tetapi berdampak nyata pada kehidupan sosial. Pemuka agama bukan aktor pinggiran, melainkan bagian penting dari ekosistem kebijakan publik.
Dalam konteks negara yang semakin kuat dan terpusat, ruang kritik masyarakat sipil cenderung menyempit. Kecerdasan berpolitik urgen bagi pemuka agama. Kecerdasan ini bukan berarti terlibat dalam politik praktis, tetapi kemampuan membaca struktur kekuasaan secara reflektif.
Pemuka agama tidak boleh naif terhadap dinamika politik, karena naivitas justru membuka ruang kooptasi. Kedekatan dengan penguasa harus disertai kesadaran akan potensi penyalahgunaan simbol agama.
Dalam tradisi keislaman, prinsip nasihat dan amar ma’ruf nahi munkar menuntut keberanian moral untuk menjaga jarak kritis. Tanpa jarak tersebut, agama berisiko kehilangan otonomi etisnya.
Bangsa, dalam wacana politik kemanusiaan, sering digambarkan sebagai entitas yang harus dilindungi dan disatukan. Narasi persatuan memang penting, tetapi tidak boleh menyingkirkan perbedaan dan kritik. Persatuan yang terlalu ditekankan tanpa ruang dialog justru melahirkan kepatuhan pasif. Dalam situasi ini, perbedaan dipersepsikan sebagai ancaman, bukan sebagai sumber koreksi. Agama seharusnya menjadi ruang aman bagi ekspresi moral yang jujur, bukan sekadar alat harmonisasi simbolik.
Pemuka agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa persatuan tidak dibangun di atas pembungkaman. Kemanusiaan membutuhkan keberanian untuk tidak selalu sepakat.
Politik kemanusiaan tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai pemulihan makna hidup masyarakat. Krisis sosial seringkali disertai dengan krisis makna yang membuat individu merasa tidak berdaya dan kehilangan orientasi.
Dalam perspektif psikologi spiritual, dimensi transendensi berperan penting dalam membentuk ketahanan mental individu dan komunitas (Al Kamil et al, 2025).
Spiritualitas memungkinkan manusia menafsirkan penderitaan bukan sekadar sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari proses eksistensial yang bermakna. Dengan demikian, politik kemanusiaan seharusnya tidak hanya menyentuh tubuh sosial, tetapi juga jiwa kolektif bangsa.
Di titik inilah peran pemuka agama menjadi strategis sebagai fasilitator makna, bukan sekadar perpanjangan tangan kebijakan negara.
Relasi pemuka agama dan negara pasca satu abad NU berada pada titik krusial. Tantangannya bukan memilih antara harmoni atau oposisi, melainkan menjaga keseimbangan antara keduanya. Negara membutuhkan legitimasi moral, tetapi legitimasi tersebut harus tetap terbuka terhadap koreksi.
Agama membutuhkan ruang dialog, tetapi dialog tanpa jarak kritis akan melemahkan fungsi etisnya. NU, dengan modal sosial dan kultural yang besar, memiliki tanggung jawab sejarah untuk menjaga keseimbangan ini.
Pemuka agama tidak cukup menjadi pilar stabilitas bangsa, tetapi juga harus menjadi penjaga nurani kemanusiaan. Sebab, negara mungkin bisa kuat tanpa kritik, tetapi masyarakat tidak akan adil tanpa keberanian moral.