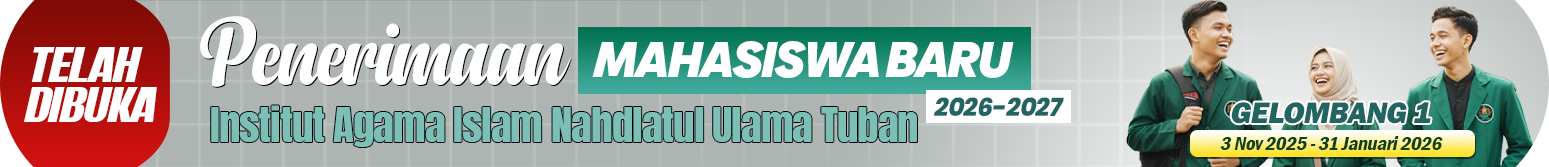Oleh : Auliya Urokhim M.A.
IAINUonline – Pidato Presiden Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyebut kekuatan ulama dan kiai sebagai penopang moral bangsa kembali menempatkan relasi agama dan negara di pusat perhatian publik.
Di tengah sorotan terhadap kebijakan sosial yang menyasar kelompok rentan, pernyataan tersebut bukan sekadar pesan normatif, melainkan sinyal politik yaitu negara membutuhkan legitimasi moral agama untuk menopang agenda kesejahteraan nasional.
Pernyataan ini menjadi relevan ketika dibaca bersamaan dengan momentum “Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU)”, organisasi keagamaan dengan basis sosial terbesar di Indonesia.
Dalam konteks itu, relasi ulama dan negara tidak lagi semata persoalan simbolik, tetapi menyentuh wilayah praksis sejauh mana agama dilibatkan dalam memastikan kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Islam Kebangsaan dan Akar Sosial NU
Sejarah NU menunjukkan bahwa relasi dengan negara selalu dibangun dalam bingkai kebangsaan. Islam kebangsaan yang dipraktikkan NU bukan Islam yang menjauh dari negara, tetapi juga bukan Islam yang larut di dalam kekuasaan. NU tumbuh dari kesadaran bahwa negara adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuannya tetap kemaslahatan umat dan perlindungan martabat manusia.
Dalam perjalanan sejarahnya, NU berperan sebagai penyangga moral sekaligus kekuatan sosial. Pesantren, masjid, dan jaringan kiai menjadi simpul penting yang menjaga kohesi sosial, terutama di wilayah-wilayah yang kerap luput dari perhatian negara.
Oleh Karena itu, ketika negara berbicara tentang kesejahteraan, termasuk melalui program MBG, NU dan ulama tidak dapat diposisikan sekadar sebagai pendukung simbolik, melainkan sebagai mitra kritis yang memahami realitas akar rumput.
MBG dan Dimensi Moral Kebijakan
Program Makan Bergizi Gratis kerap dipahami sebagai kebijakan teknokratis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Namun dalam konteks sosial Indonesia, kebijakan semacam ini tidak pernah netral nilai. Ia bersentuhan langsung dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan akses dasar terhadap layanan publik.
Ketika Presiden menautkan MBG dengan peran ulama dan kiai, terdapat pengakuan implisit bahwa kebijakan kesejahteraan memerlukan legitimasi moral. Ulama dipandang memiliki kedekatan dengan masyarakat miskin dan memahami dampak nyata kebijakan di tingkat paling bawah.
Namun di sinilah letak ujian relasi ulama dan negara apakah ulama hanya diminta menguatkan narasi, atau dilibatkan dalam proses koreksi kebijakan?
Islam kebangsaan kehilangan maknanya jika berhenti pada dukungan retoris. Ia baru menemukan relevansinya ketika agama berani memastikan bahwa kebijakan publik tidak melenceng dari tujuan keadilan sosial.
Negara Kuat dan Risiko Penyempitan Ruang Kritis
Pemerintahan di era Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan gagasan negara kuat, stabilitas nasional, dan efektivitas kebijakan. Dalam batas tertentu, stabilitas memang menjadi prasyarat bagi pembangunan sosial. Namun negara yang kuat juga membawa risiko yakni menyempitnya ruang kritik masyarakat sipil, termasuk suara ulama.
Dalam tradisi keislaman, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemberi legitimasi, tetapi juga sebagai penjaga etika kekuasaan. Prinsip nasihat dan amar ma’ruf nahi munkar menempatkan ulama sebagai aktor moral yang harus menjaga jarak kritis dengan negara. Kedekatan yang terlalu rapat berpotensi melemahkan fungsi korektif tersebut. Oleh karena itu, ketika ulama diposisikan sebagai “kekuatan negara”, pertanyaan pentingnya Adalah kekuatan untuk siapa dan untuk tujuan apa?
NU sebagai Civil Society
NU secara historis menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil. Ia tidak alergi terhadap negara, tetapi juga tidak larut dalam politik kekuasaan. Posisi ini memungkinkan NU menjadi jembatan antara negara dan masyarakat, terutama kelompok mustadh‘afin.
Dalam konteks kebijakan kesejahteraan seperti MBG, peran NU menjadi krusial. Ulama dan kiai berada di garis depan untuk memastikan bahwa program tidak berhenti pada angka dan laporan, tetapi benar-benar menjangkau anak-anak di desa, wilayah pinggiran, dan daerah tertinggal. Di sinilah relasi dialogis antara ulama dan negara menemukan maknanya.
Menjaga Jarak, Merawat Dialog
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa menjaga jarak kritis dengan kekuasaan bukan berarti bersikap oposisi permanen. Jarak justru memungkinkan dialog yang jujur. NU pernah menunjukkan kemampuan ini ketika menempatkan diri sebagai kekuatan moral, bukan alat politik praktis.
Pasca satu abad NU, tantangan menjadi semakin kompleks. Populisme agama, politik identitas, dan tekanan kepentingan ekonomi global menuntut konsistensi moral yang lebih kuat. Jika ulama terlalu larut dalam harmoni simbolik dengan negara, risiko yang muncul adalah tumpulnya suara kritis.
Islam kebangsaan tidak boleh direduksi menjadi slogan persatuan tanpa keadilan. Ia harus hadir sebagai etika publik yang berani mengoreksi kebijakan ketika menyimpang dari tujuan kesejahteraan.
Pidato Presiden tentang MBG dan kekuatan ulama membuka ruang refleksi penting tentang arah relasi agama dan negara di Indonesia. Di satu sisi, negara membutuhkan legitimasi moral untuk menjalankan kebijakan kesejahteraan. Di sisi lain, ulama membutuhkan jarak kritis agar tetap menjadi penjaga nurani publik.
Relasi ulama dan negara pasca satu abad NU berada di titik krusial. Tantangannya bukan memilih antara harmoni atau kritik, melainkan memastikan keduanya berjalan beriringan. NU, dengan modal sosial dan kulturalnya, memiliki tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa agama tetap menjadi sumber etika public dan bukan sekadar ornamen kekuasaan. Sebab, negara mungkin bisa kuat tanpa kritik, tetapi masyarakat tidak akan adil tanpa keberanian moral.