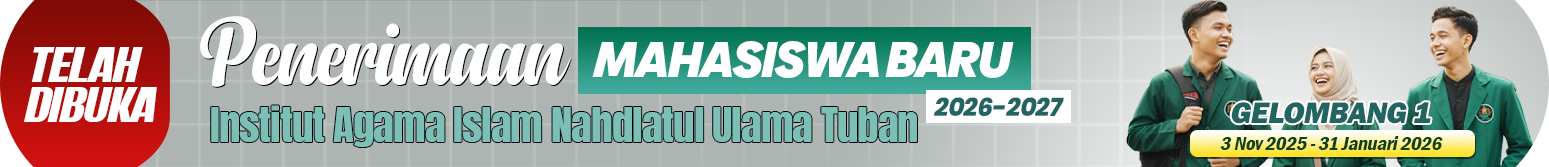Oleh : Agus Ali Sururi
Di ujung bulan kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia, kita melihat banyak sekali peristiwa yang membuat “takjub” dengan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Di awal bulan kemerdekaan kita melihat banyak sekali bendera film anime One Piece berkibar di berbagai daerah, yang diawali dari satu bendera one piece berkibar di belakang truk sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah terkait pelarangan truk ODOL (over-dimension, overload).
Kemudian disusul di berbagai daerah banyak yang mengibarkan bendera one piece di bawah bendera merah putih sebagai bentuk ungkapan masyarakat Indonesia terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Belum selesai pada pengibaran bendera one piece kejutan selanjutnya berasal dari Kabupaten Pati, ribuan masyarakat Pati mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Pati. Ini berawal dari kebijakan bupati yang menaikkan tarif PBB sebesar 250 % dari tahun sebelumnya, dan beberapa kejutan lain.
Di sini saya tidak akan memberikan tanggapan terhadap “kejutan-kejutan” di atas, saya kembali teringat dengan pengertian merdeka yang ada di buku LKS semasa sekolah dulu, dalam LKS bahasa, “merdeka” berarti bebas: tidak dijajah, tidak terikat.
Kata ini berasal dari maharddhika dalam bahasa Sanskerta–orang yang sejahtera, tuan bagi dirinya sendiri. Secara linguistik, makna ini lebih lugas: merdeka berarti tak ada rantai yang membelenggu. Tetapi dalam buku LKS sejarah memberi warna yang lebih tegas. Sejarawan akan berkata: merdeka adalah saat bangsa ini berhasil melepaskan diri dari penjajahan, berdiri di kaki sendiri, menentukan nasib tanpa komando asing.
Di saat fokus membaca LKS, di layar televisi muncul film animasi Nussa yang diproduksi oleh studio The Little Giantz dan Visinema Pictures, studio yang sama pengarap film animasi Jumbo. Film ini disutradarai oleh Bony Wirasmono.
Pada episode ini Nussa tersenyum puas, karena selama beberapa hari, rumahnya terasa seperti taman bermain pribadi. Tidak ada suara Umma yang cerewet mengingatkan Nussa untuk merapikan mainannya. Tidak ada jadwal ketat untuk belajar, dan tidak ada lagi ‘peta berjalan’ yang selalu tahu di mana letak buku matematikanya. Ia “merdeka” dari semua aturan itu, dan kemerdekaan itu terasa begitu manis.
Ia bebas bermain video game sampai larut, memakan makanan ringan dan softdrink, meninggalkan piring bekas makan di meja, dan bahkan membiarkan kaus kakinya berserakan di ruang tengah. Ini adalah surga. Rarra pun merasakan hal yang sama. Mereka bisa menonton film apa pun yang mereka suka tanpa ada batasan. Rumah terasa sunyi, namun Nussa menganggapnya damai.
Saya tersenyum getir. Karena di kampus, saya juga kadang begitu. Tidak ada yang menegur, tidak ada aturan yang benar-benar ditegakkan. Saya bisa masuk seenaknya, pulang sesukanya, menyusun laporan sambil setengah hati, atau bahkan menunda pekerjaan dengan alasan klise. Merdeka, kataku.
Namun, perlahan, keheningan itu berubah menjadi kekosongan. Suatu sore, Rarra merengek karena tidak bisa tidur. Nussa, yang biasanya bisa mengandalkan Umma untuk mendongeng, mencoba bercerita. Ia mengarang cerita tentang pahlawan super, tetapi ceritanya terasa datar dan hambar. Rarra tidak tertawa, ia hanya menatap Nussa dengan mata berkaca-kaca.
“Nussa, kenapa ceritamu tidak seasyik cerita Umma?” tanyanya polos.
Nussa terdiam. Ia baru menyadari bahwa kemerdekaan yang ia nikmati adalah kemerdekaan yang hampa. Piring yang berantakan, kamar yang berantakan, dan kaus kaki yang berserakan bukanlah tanda kebebasan, melainkan kekacauan. Ia bisa melakukan semua yang ia mau, tapi tidak ada lagi tangan lembut yang merapikan kekacauan itu.
Saya pun terdiam: bukankah yang saya nikmati di kampus juga semacam kemerdekaan hampa? Saya bebas dari teguran atasan, bebas dari kewajiban yang ditegakkan ketat, tapi pelan-pelan saya jadi tawanan diri sendiri—tawanan malas, tawanan abai, tawanan gengsi yang sok sibuk.
Nussa menatap ke luar jendela. Halaman rumah yang biasanya penuh dengan tawa kini terasa sepi. Ia merindukan teriakan Umma yang memanggilnya; “Nussa, sudah sore, waktunya mandi!”
Ia merindukan bekal makan siang buatan Umma yang selalu terasa lezat, bahkan jika isinya hanya roti dan telur. Ia merindukan kehangatan dari keberadaan Umma yang cerewet, yang selalu ada.
Ternyata kemerdekaan itu bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan berani bertanggung jawab pada apa saja yang kita lakukan? Delapan puluh tahun bangsa ini merdeka, tapi aku masih menjadi penjajah bagi jam kerjaku sendiri. Aku menjarah produktivitasku, aku membakar waktu seperti membakar kemenyan untuk diri sendiri, berharap harum padahal cuma bikin sesak.
Jika Nussa saja bisa tersentak belajar dari kehilangan bunda, kenapa aku yang sudah dewasa tidak bisa tersentak oleh hilangnya waktu? Barangkali karena waktuku tidak pernah memprotes. Tidak pernah menggugat di meja rapat. Tidak pernah mengirim surat peringatan.
Maka izinkan aku menegur diriku sendiri: Hei, jangan terlalu bangga menjadi pegawai tanpa absen, pekerja tanpa jam, manusia tanpa teguran. Karena diam-diam engkau bukan merdeka, tapi sekadar tidak diawasi. Dan bedanya tipis sekali—seperti bedanya merdeka dengan pura-pura merdeka.