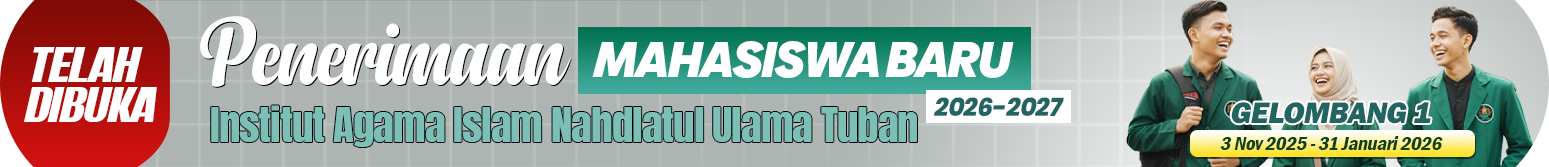Oleh: Agus Fathoni Prasetyo
Dalam lanskap sosial yang terus berubah, pemahaman terhadap perilaku manusia menjadi kunci penting untuk membaca dinamika masyarakat. Salah satu teori yang masih relevan hingga kini adalah teori kebutuhan Abraham Maslow, yang diperkenalkan pada tahun 1943 melalui tulisannya “A Theory of Human Motivation”.
Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan yang tersusun secara hierarkis: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri (Maslow, 1943).
Meskipun telah berusia lebih dari delapan dekade, teori ini tetap menjadi alat analisis yang berguna untuk memahami kondisi masyarakat modern, terutama dalam mengidentifikasi pergeseran orientasi hidup dan nilai-nilai sosial.
Dalam masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi, kebutuhan manusia tidak lagi dapat dipahami secara sederhana. Meski demikian, struktur hierarkis Maslow justru memberikan kerangka reflektif yang kuat untuk membaca kompleksitas tersebut.
Pada tataran kebutuhan fisiologis, masyarakat modern memang tampak lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Namun, di balik kemudahan akses itu, muncul problematika baru berupa ketimpangan ekonomi, krisis pangan di wilayah tertentu, serta gaya hidup konsumtif yang justru mengancam keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam jangka panjang.
Data BPS 2023 mencatat bahwa sekitar 9,36% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, gaya hidup kelas menengah ke atas menunjukkan tren konsumtif yang luar biasa: makanan cepat saji, kopi susu kekinian, dan liburan ke luar negeri menjadi bagian dari keseharian.
Terjadi kesenjangan yang lebar antara kelompok yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan mereka yang sudah berpikir tentang “self reward” setiap akhir pekan. Artinya, pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi isu serius dalam pembangunan kita.
Selanjutnya, kebutuhan akan rasa aman menjadi semakin krusial dalam konteks masyarakat modern. Keamanan tidak lagi hanya dimaknai sebagai perlindungan dari bahaya fisik, tetapi juga mencakup keamanan ekonomi, kesehatan, dan informasi.
Masyarakat urban Indonesia saat ini hidup dalam situasi yang paradoks: teknologi membuat segalanya terasa mudah, tapi juga penuh risiko. Ketergantungan pada platform digital memperbesar ancaman peretasan data pribadi, penipuan online, hingga ketidakpastian pekerjaan.
Sementara itu, perlindungan sosial belum sepenuhnya merata. Meski BPJS Kesehatan telah menjadi langkah maju, pelayanan dan aksesibilitasnya masih menjadi tantangan di banyak daerah. Rasa aman, dalam hal ini, bukan hanya soal fisik, tapi juga soal ketenangan pikiran dan banyak masyarakat kita yang belum mencapainya.
Kebutuhan sosial—yang mencakup cinta, afiliasi, dan rasa memiliki—mengalami transformasi besar di era digital. Masyarakat modern hidup dalam jejaring sosial yang luas, namun juga menghadapi isolasi eksistensial yang tinggi. Interaksi yang semula bersifat langsung dan emosional, kini sering kali tergantikan oleh komunikasi virtual yang cepat namun dangkal.
Banyak individu merasa terhubung secara digital, tetapi terputus secara emosional. Seperti halnya masyarakat Indonesia menjadi salah satu pengguna terbesar platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp.
Kita tampaknya makin terhubung, tapi dalam banyak kasus, justru makin merasa kesepian. Fenomena ini disebut oleh Turkle (2011) sebagai “alone together”—bersama secara fisik atau digital, tapi tidak benar-benar hadir secara emosional. Banyak orang muda mengalami FOMO (fear of missing out), merasa harus selalu eksis secara daring, tapi secara batin merasa hampa.
Kebutuhan akan relasi sosial yang bermakna makin sulit terpenuhi di tengah budaya “scroll and skip”. Maslow menekankan bahwa kebutuhan akan afiliasi adalah fondasi psikologis penting bagi manusia, dan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi secara otentik, maka muncul kecenderungan pada alienasi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental.
Tingkatan berikutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan (esteem), menjadi sorotan utama dalam masyarakat modern yang kompetitif. Pengakuan sosial, prestise, dan pencapaian pribadi kini menjadi tolok ukur nilai diri.
Namun, dalam praktiknya, kebutuhan ini sering kali dimanipulasi oleh logika kapitalisme dan budaya populer yang menekankan citra, bukan esensi. Media sosial, misalnya, menciptakan ilusi pencapaian dan popularitas, yang mendorong banyak individu untuk terus membandingkan diri dan mencari validasi eksternal.
Akibatnya, kebutuhan akan penghargaan justru berubah menjadi tekanan psikologis yang melelahkan. Kebutuhan akan penghargaan (esteem) menjadi semakin kompleks di masyarakat modern.
Di satu sisi, ada pencapaian nyata—seperti pendidikan tinggi, karier yang mapan, atau kontribusi pada masyarakat. Tapi di sisi lain, muncul budaya “likes” dan “followers” yang mengaburkan makna dari penghargaan sejati.
Validasi eksternal menjadi kebutuhan yang makin dominan, bahkan menggeser motivasi intrinsik. Ini sejalan dengan kritik Fromm (2001) terhadap masyarakat modern yang lebih mementingkan “to have” daripada “to be”.
Puncak dari hierarki Maslow adalah aktualisasi diri, yakni pencapaian potensi tertinggi sebagai manusia. Dalam masyarakat modern, kesempatan untuk mencapai aktualisasi diri memang terbuka lebar melalui pendidikan, kebebasan berekspresi, dan berbagai bentuk kreativitas.
Namun, aktualisasi diri juga menjadi semacam “proyek individualistis” yang kerap terpisah dari tanggung jawab sosial. Padahal, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, aktualisasi sejati seharusnya turut memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keberlanjutan.
Teori Maslow mengajarkan kita bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari ekonomi atau teknologi, tapi juga dari terpenuhinya seluruh dimensi kebutuhan manusia secara berimbang.
Dalam konteks Indonesia, pembangunan manusia harus diarahkan tidak hanya pada pencapaian angka makro—seperti pertumbuhan ekonomi atau indeks digitalisasi—tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan yang memanusiakan, kebijakan publik yang adil, dan budaya yang sehat secara emosional adalah jalan menuju masyarakat yang benar-benar maju.
Sebagai akademisi dan bagian dari masyarakat kampus, kita memiliki peran penting untuk mengkritisi sekaligus menawarkan solusi atas realita ini. Kampus bukan hanya ruang belajar teori, tetapi juga tempat untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan, membangun solidaritas, dan mendukung proses aktualisasi diri yang bermakna.(*)